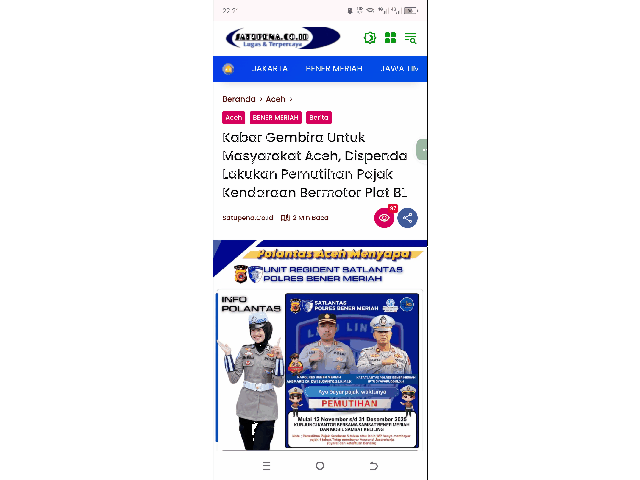Opini Oleh: Prof. Dr. Zulfikar Ali Buto Siregar, S.Pd.I., M.A,Direktur Pascasarjana UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Lhokseumawe, satupena.co.id – Setiap datangnya musim hujan dengan curah yang tinggi, masyarakat di berbagai wilayah baik perkotaan maupun pedesaan di Indonesia seakan kembali dihadapkan pada siklus tahunan yang melelahkan, yakni bencana banjir. Bunyi hujan yang sejatinya identik dengan keberkahan dan kesuburan kini kerap menghadirkan rasa cemas dan ketakutan. Namun, apabila dicermati secara lebih mendalam, banjir tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis berupa saluran drainase yang tidak berfungsi atau anomali cuaca ekstrem. Banjir merupakan refleksi besar dari kondisi moral kolektif masyarakat, terutama terkait tingkat kepedulian sosial manusia terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Setiap kenaikan permukaan air menyimpan pesan etis yang mendesak untuk direnungkan oleh seluruh lapisan sosial tanpa terkecuali.
Selama ini, banjir kerap direduksi sebagai kegagalan infrastruktur atau sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Memang tidak dapat disangkal bahwa lemahnya tata kelola perkotaan serta praktik korupsi dalam proyek pengelolaan sungai turut memperparah situasi. Namun, kecenderungan untuk menyalahkan pihak lain tanpa disertai refleksi diri merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab moral. Kepedulian sosial berakar pada kesadaran bahwa setiap tindakan individual memiliki dampak kolektif. Membuang sampah kecil ke selokan mungkin terasa tidak berarti, tetapi ketika dilakukan secara masif, akumulasi perilaku tersebut menjelma menjadi bencana ekologis. Inilah inti krisis moral yang kita hadapi, memudarnya kesadaran akan konsekuensi sosial dari tindakan personal. Masyarakat kerap terjebak dalam kepedulian yang sempit, terbatas pada ruang privat, sembari mengabaikan kondisi lingkungan di luar batas kepentingan pribadi.
Perspektif sosiologis, banjir juga menyingkap kesenjangan empati yang nyata. Kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan mapan dengan perlindungan infrastruktur memadai sering kali hanya menyaksikan banjir sebagai tayangan media. Sebaliknya, warga di bantaran sungai dan permukiman padat harus menghadapi risiko kehilangan nyawa dan harta setiap kali air meluap. Dalam konteks ini, kepedulian sosial menuntut kesadaran bahwa keselamatan lingkungan merupakan nasib bersama. Tidak ada individu atau kelompok yang benar-benar aman selama pihak lain masih berada dalam ancaman. Banjir menjadi pengingat bahwa egoisme kolektif mentalitas yang hanya mementingkan keamanan diri sendiri merupakan penghalang utama terciptanya keselamatan bersama.
Lebih dari itu, banjir menguji keaslian nilai gotong royong yang selama ini menjadi kebanggaan nasional. Meski solidaritas sering muncul saat bencana telah terjadi, kepedulian tersebut kerap bersifat sementara dan reaktif. Padahal, moralitas sosial yang substansial seharusnya terwujud dalam tindakan preventif dan berkelanjutan. Perubahan gaya hidup ramah lingkungan seperti mengurangi plastik sekali pakai, menanam vegetasi, dan mengelola limbah rumah tangga merupakan bentuk kepedulian yang lebih mendasar dibandingkan bantuan darurat semata. Dalam kerangka ini, konsep kebaikan perlu didefinisikan ulang secara ekologis, yakni sebagai perilaku yang tidak menambah beban risiko bagi orang lain.
Banjir juga menyingkap paradoks dalam cara manusia memandang alam. Alam sering diperlakukan sebagai objek eksploitasi demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Alih fungsi lahan resapan menjadi kawasan komersial mencerminkan pengabaian etika lingkungan. Kepedulian sosial sejatinya mencakup tanggung jawab lintas generasi. Kerusakan ekosistem yang kita lakukan hari ini adalah perampasan hak hidup yang layak bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, banjir dapat dipahami sebagai konsekuensi ekologis atas ketidakseimbangan yang diciptakan manusia. Selama tanah hanya dilihat sebagai komoditas, bukan sebagai sistem kehidupan yang perlu dijaga, pesan moral dari bencana ini akan terus berulang.
Setiap peristiwa banjir juga mempertaruhkan martabat kemanusiaan. Kehilangan tempat tinggal, dokumen penting, dan sumber penghidupan meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Kepedulian sosial menuntut solidaritas yang melampaui sekat-sekat identitas. Ironisnya, sering kali diperlukan bencana besar untuk mengingatkan manusia akan nilai kemanusiaan. Seharusnya, kesadaran akan kerentanan hidup di tengah krisis iklim mendorong terbentuknya sistem sosial dan kebijakan publik yang lebih inklusif, protektif, dan berpihak pada kelompok rentan.
Banjir juga menjadi ujian integritas, baik bagi pemimpin maupun warga negara. Bagi pengambil kebijakan, bencana ini menguji komitmen terhadap transparansi anggaran dan konsistensi penegakan aturan tata ruang. Pemberian izin pembangunan di kawasan terlarang demi kepentingan tertentu merupakan pengkhianatan moral terhadap keselamatan publik. Sementara itu, ketaatan warga terhadap regulasi lingkungan adalah kontribusi nyata bagi ketertiban sosial. Ketika integritas individu runtuh, ketahanan sosial pun ikut melemah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesepakatan sosial baru yang menempatkan keadilan ekologis sebagai fondasi utama kehidupan bersama.
Ranah pendidikan, banjir seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran moral bagi generasi muda. Pendidikan yang terlalu menekankan aspek kognitif tanpa membangun kepekaan afektif terhadap lingkungan berisiko melahirkan generasi yang abai. Menanamkan kepedulian terhadap sungai dan alam sejak dini berarti menumbuhkan empati sosial. Kesadaran bahwa merusak lingkungan sama dengan mencederai sesama merupakan fondasi bagi masyarakat yang beradab. Kepedulian sosial bukan sekadar materi ajar, melainkan nilai yang harus dihidupkan melalui keteladanan.
Akhirnya, merenungkan banjir sebagai pelajaran moral mengharuskan kita meninjau ulang makna kemajuan. Sebuah kota tidak layak disebut maju apabila pembangunan fisiknya berdiri di atas penderitaan warganya. Kemajuan sejati tercapai ketika pembangunan dan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kelompok paling rentan. Etika kepedulian menuntut pergeseran paradigma dari dominasi atas alam menuju relasi kemitraan dengannya. Banjir mengingatkan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem, bukan penguasanya. Ketika keseimbangan itu dirusak, bencana menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Untuk itu anjir bukan sekadar persoalan air yang memasuki ruang hidup manusia, melainkan teguran moral atas melemahnya rasa kepedulian. Ia merupakan panggilan untuk keluar dari sikap egoistik dan mulai mempertimbangkan dampak setiap tindakan terhadap lingkungan sosial dan alam. Kepedulian sosial yang lahir dari refleksi atas bencana harus menjadi kekuatan transformatif mengubah cara berpikir, pola konsumsi, dan relasi antar manusia. Setiap genangan air seharusnya menjadi pengingat akan tanggung jawab moral yang belum sepenuhnya ditunaikan. Banjir tidak boleh berhenti sebagai peristiwa rutin tahunan, melainkan harus menjadi momentum perbaikan karakter dan kesadaran kolektif bangsa. (Y)