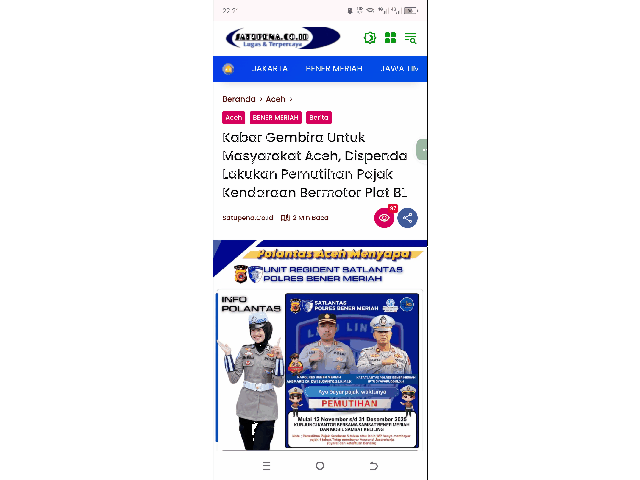Opini: Oleh Yusrizal
Satupena.co.id-Aceh Utara dan Lhokseumawe dua wilayah ini sejak lama dikenal sebagai pusat kejayaan migas Aceh. Ladang-ladang besar berdiri di sana, pipa-pipa baja terus mengalirkan gas menuju industri, dan pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa Aceh adalah “lumbung energi” Indonesia. Namun di balik gemerlap angka produksi dan narasi kebanggaan itu, ada kenyataan getir yang menampar akal sehat: masyarakat di daerah penghasil gas justru harus berebut tabung Elpiji 3 kilogram layaknya berebut sembako pada masa darurat.
Di sejumlah gampong, antrean tabung melon bukan lagi pemandangan baru. Warga sudah hapal polanya: truk datang, kerumunan mengular, tabung diturunkan, dan tak lama kemudian habis sebelum semua warga kebagian. Keluhan mengemuka di banyak titik. Ada ibu rumah tangga yang harus menghentikan aktivitas dapur berhari-hari, ada pedagang kecil terpaksa menutup lapak lebih cepat karena gas tak tersedia. Semua ini terjadi di wilayah yang ironisnya berdiri di atas sumur-sumur gas raksasa.
Pertanyaan pedas pun bergema dari masyarakat: apa gunanya menjadi daerah penghasil energi jika penduduknya sendiri harus berjuang setengah mati untuk mendapatkan satu tabung gas bersubsidi? Pertanyaan itu menggantung seperti asap dari tungku yang tak bisa menyala.
Dugaan permainan harga dan manipulasi distribusi makin lantang dibicarakan. Beberapa warga mengaku tabung sering “hilang” sebelum tiba di pangkalan. Ada pula dugaan bahwa pangkalan memilih menjual kepada pembeli dalam jumlah besar dengan harga lebih tinggi, sehingga stok untuk rakyat kecil terpangkas. Ketika sampai ke tangan warga, harganya sudah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara itu, pihak terkait hanya mengeluarkan imbauan—tanpa langkah nyata yang dirasakan publik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, wajar bila publik mempertanyakan:
Di mana fungsi pengawasan pemerintah daerah? Siapa pemain yang mengendalikan distribusi Elpiji 3 kilogram di Aceh Utara dan Lhokseumawe? Mengapa pola yang sama berulang dari tahun ke tahun tanpa satu pun aktor yang dimintai pertanggungjawaban?
Kelangkaan gas bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah gejala lemahnya tata kelola energi: tidak transparan, tidak disiplin, dan terlalu mudah dipermainkan segelintir pelaku. Masyarakat sudah berkali-kali menyuarakan keresahan, namun yang kembali diterima hanyalah janji penertiban, rapat koordinasi, atau pernyataan normatif yang menguap tanpa hasil.
Sebagian warga bahkan merasa seperti menjadi penonton dari drama panjang yang tak pernah selesai. “Wilayah kami ini pusat gas. Tapi untuk memasak pun kami harus menunggu nasib,” begitu keluhan yang kerap terdengar.
Aceh Utara dan Lhokseumawe seharusnya menjadi contoh daerah yang menikmati keberlimpahan energi, bukan simbol kelangkaan. Namun selama pemerintah tidak membuka secara transparan rantai distribusi, tidak mengaudit agen dan pangkalan secara serius, serta tidak menindak tegas oknum yang mempermainkan barang subsidi, maka tabung gas 3 kilogram akan tetap menjadi barang mewah di tanah sendiri.
Di daerah yang disebut kaya gas, rakyat kecil tidak seharusnya berdiri dalam antrean panjang hanya demi menyalakan dapur mereka. Karena ironi paling pahit bukan terletak pada kurangnya gas—melainkan pada lemahnya keberpihakan kepada mereka yang paling berhak merasakan manfaatnya.